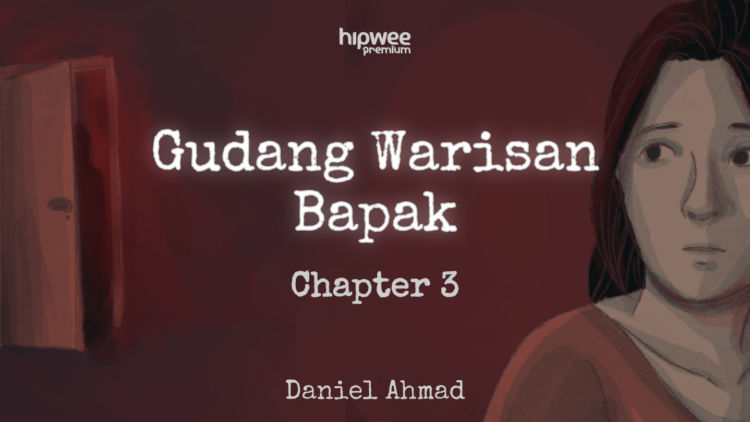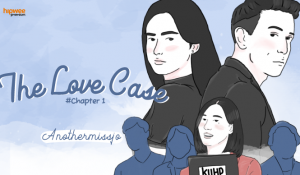Kamar bapak/ Illustration by Hipwee
Aku urung mengetuk pintu kamar, karena ternyata tidak dikunci. Lebih tepatnya tidak ditutup rapat. Pelan kudorong daun pintu dengan bahu, sambil tetap menjaga agar sup sayur di atas nampan tidak tumpah dari mangkoknya.
“Bapak,” panggilku.
Bapak ada di kamar. Tidur miring membelakangiku. Jelas kudengar suara dengkur, tapi jemari kaki bapak bergerak-gerak seperti tidak sedang tidur. Konsentrasiku tidak lagi pada kehati-hatian membawa makanan, tapi lebih kepada langkah kaki yang tidak ingin menginjak kotoran. Permukaan lantai semen penuh bercak cairan kental yang sedikit mengering. Seperti bekas muntah kemarin. Aku tidak akan kaget lagi kalau di sudut kamar berdebu itu ada kotoran manusia, mengingat sepertinya bapak sudah lama tidak mandi. Lupakan tentang salat, bapak mungkin juga sudah lama tidak menyentuh air.
Tak ada tempat meletakkan makanan. Kupegang erat sambil menerawang seisi kamar. Pandangan mengedar ke segala sisi dan sudut. Dari manapun kulihat, ruangan ini masih 99% gudang. Adanya bapak hanyalah 1% yang membuat ruangan ini terlihat seperti kamar. Satu hal yang pasti, yakni tidak ada tanda-tanda orang lain tidur di sini selain bapak.
“Jadi … yang kulihat kemarin itu benar-benar cuma khayalan,” gumamku.
Saat itu lampu dapur mati. Gelap. Aku juga lelah. Kutumpuk beragam alasan untuk mendukung asumsiku bahwa sosok itu memang tidak ada.
“Zara.”
Nyaris aku tumpahkan makanan di atas nampan. Suara bapak sama sekali tidak keras; tidak dalam level yang bisa mengejutkan orang. Aku saja yang sedang bengong, hingga suara bapak terdengar seperti bunyi alarm yang membawaku kembali ke alam sadar.
“Ba-bapak.”
Bapak sudah duduk di atas ranjang. Tangan dan kakinya bergerak-gerak tanpa makna. Kadang menggaruk anggota tubuhnya yang gatal, kadang menyentuh kedua pipinya yang cekung, kadang menempelkan kedua telapak tangannya seperti orang sedang berdoa.
“Bapak makan dulu, ya,” kataku.
Aku duduk di ranjang beralas kardus bekas. Sama sekali tak ada kelembutan. Aku memilih tidur di lantai dari pada di ranjang penuh derita seperti ini. Kuletakkan nampan di sisi ranjang, di bawah kaki bapak yang kini sudah menekuk, memberi ruang.
“Mau Zara suapin?” tanyaku.
Bapak menggeleng.
“Taruh saja di situ,” jawabnya.
“Tapi beneran dimakan ya, Pak,” rayuku.
Bapak tidak menjawab. Reaksinya sedikit aneh. Setelah berkali-kali mengeluh lapar sampai seperti tadi malam, sekarang bapak malah terkesan tidak punya nafsu untuk menyentuh masakanku.
Setelah diam sejenak, akhirnya kuputuskan untuk pergi dari kamar bapak. Bapak sedang dalam kondisi yang tidak bisa diajak bicara. Mungkin nanti aku akan kembali lagi. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan padanya.
***
Siang hari kududuk di halaman rumah, setelah menyapu daun-daun mangga kering yang nyaris menutupi seluruh halaman. Udara pedesaan ini sangat aku rindukan, segar dan sejuk meski di bawah terik siang. Sangat berbeda dengan udara di kota. Satu-satunya hal yang membuatku tak nyaman adalah lirikan tetangga yang lewat. Sudah empat orang yang lewat, sudah kucoba juga untuk menyapa dengan ramah, tapi mereka cenderung menghindar. Bahkan ada yang berbisik-bisik satu sama lain sambil melirik ke arahku.

Bisik-bisik/ Illustration by Hipwee
Merasa kedamaianku terganggu, kuputuskan untuk masuk ke rumah. Saat itulah Kak Rohim datang. Suara motornya lebih ribut dari mesin penggiling jagung.
“Hai, Ra,” sapanya.
“Ya, Kak. Pulang kerja?”
“Lagi istirahat. Dua puluh menit lagi mesti balik. Kamu sudah makan?”
“Sudah barusan. Kakak?”
Diamnya Kak Rohim sudah cukup memperjelas maksud kedatangannya. Dia lapar. Ini jam istirahat dan mungkin ia tidak punya uang untuk jajan di kantin tempatnya kerja.
“Aku masak banyak hari ini. Kakak makan dulu sana!”
Kak Rohim mengangguk. Terlukis senyum lega di wajahnya.
Selesai makan siang, masih ada waktu sepuluh menit bagi Kak Rohim untuk merokok. Kutemani ia di teras rumah. Lagi-lagi tetangga yang lewat menampakkan ekspresi yang sama. Mereka seperti takut atau sedikit jijik melihat kami.
“Tetangga pada kenapa ya, Kak? Tadi aku nyapa Bu Farida yang kebetulan lewat, aku yakin dia masih ingat aku, tapi lagaknya seperti nggak kenal gitu.”
“Bukan salah kamu, Ra.”
“Terus?”
Kak Rohim mengepul asap ke udara. Mengosongkan mulutnya dari asap tembakau lalu kembali bicara.
“Dulu … Bapak itu sering banget keluyuran di desa ini kalau malam. Dia … dia minta makan gitu sama tetangga, tapi cara mintanya yang bikin tetangga kita benci.”
Aku bisa menebak ke mana maksud dari perbincangan ini.
“Bapak minta-minta ke tetangga? Kalian nggak ngasih bapak makan?” hardikku.
“Bu-bukan gitu. Aku rutin ngirim bapak nasi. Kadang gantian sama Kak Sabit, tapi sebanyak apa pun kami kirim, sepertinya nggak cukup bikin bapak kenyang. Makanya setiap malam—tengah malam, bapak sering masuk ke dapur tetangga. Ke kamar mereka. Ngemis minta makan. Sekali dua kali tetangga kita masih bisa maklum, soalnya bapak sakit, tapi kalau setiap malam seperti itu, siapa pun pasti kesal. Aku juga jadi kena batunya.”
“Maksudnya?”
“Ya, aku dan anak-anak bapak yang lain dituduh nggak bisa ngerawat bapak. Sama seperti kamu barusan, kami dikira nggak pernah ngasih bapak makan. Padahal faktanya nggak gitu. Kami udah berunding sama pak RT, akhirnya kami sepakat untuk mencari cara biar bapak nggak keluyuran tengah malam lagi,” tutur Kak Rohim.
“Jadi karena itu pintu sama jendela di rumah ini ditutup rapat?” tanyaku.
Kak Rohim mengangguk.
Terjawab sudah satu misteri tentang kenapa rumah ini jadi seperti rumah tahanan dan kenapa juga Pak Sukril ngasih saran yang aneh tadi malam. Sinisnya tetangga-tetangga tadi juga pasti karena alasan yang sama. Meski aku memahami bagaimana terganggunya mereka sama tingkah bapak, tapi seharusnya mereka tidak melibatkan aku yang tidak tahu apa-apa ini.
“Oh, ya, Kak. Kunci kamarku yang lama ada di mana?”
Kak Rohim terbatuk-batuk. Asap rokoknya keluar secara tidak teratur dari hidung dan mulut.
“Mau ngapain?” tanyanya. Kaget dan sedikit panik.
“Mau aku bersihkan,” jawabku.
“Buat?”
“Ya, buat bapak, lah. Aku nggak tega bapak tidur di gudang, jadi sebelum aku kembali ke kota, aku pengin beresin kamar lamaku biar ditempati ba—“
“—Jangan!” seru Kak Rohim. “Jangan pernah buka kamar itu!”
Aku tercengang. Ini pertama kalinya Kak Rohim bicara dengan nada tinggi padaku.
“Kenapa?” tanyaku dengan suara sedikit bergetar.
“Aku nggak bisa kasih tahu alasannya, tapi aku serius, Ra. Jangan buka kamar itu. Setidaknya jangan sekarang.”

Kamar rahasia/ Illustration by Hipwee
Aku muak dengan segala rahasia yang satu per satu muncul. Setiap satu misteri terjawab, muncul lagi misteri yang baru. Aku tidak sepenuhnya menyalahkan mereka atas ketidaktahuanku, karena memang sudah lama aku tidak ikut campur urusan keluarga ini. Namun, sekarang aku jadi bagian dari masalah, rasanya aku punya hak untuk tahu semuanya.
“Sebenarnya ada berapa banyak, sih, yang kalian sembunyikan dari aku?”
“Bukan gitu, Ra—“
“—Halah! Kalian yang minta aku pulang seolah-olah aku benar-benar dibutuhkan, tapi sampai di sini, tetap saja nggak ada yang berubah. Aku masih saudara tiri kalian yang nggak terlalu dianggap.”
“Aku nggak bermaksud gitu, Ra.”
“Ya, terus gimana? Kok lama-lama aku malah ngerasa dimanfaatkan sama kalian?”
Aku benar-benar kesal. Sedih juga. Air mataku sampai nyaris berderai. Kak Rohim memegangi kedua pundakku. Mencoba menenangkan emosi yang meledak-ledak.
“Kak Sabit tadi sudah ke sini, kan? Dia sudah bilang kalau besok kita semua akan kumpul, kan? Aku janji, besok kami jelaskan semuanya.”
“Jelasin semuanya sekarang!” Paksaku.
Sungguh. Aku tidak ingin bermalam di sini lagi kalau masih punya perasaan bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang tidak aku tahu, dan dari cara saudara-saudaraku menyembunyikannya, sepertinya sesuatu itu sedikit berbahaya. Atau sangat berbahaya?
“Aku nggak bisa—“
“—bisa!”
“—Oke!” tegas Kak Rohim.
“Jadi, pertemuan besok adalah untuk membahas hal-hal yang harus kita selesaikan kalau-kalau suatu saat bapak meninggal,” tutur Kak Rohim dengan tenang, seolah-olah kata meninggal sudah sangat pasti, dan tak punya pengaruh apa-apa padanya.
“Apa?”
“Maksudku … besok kita akan bahas soal warisan,” pungkas Kak Rohim.
-bersambung

![]()