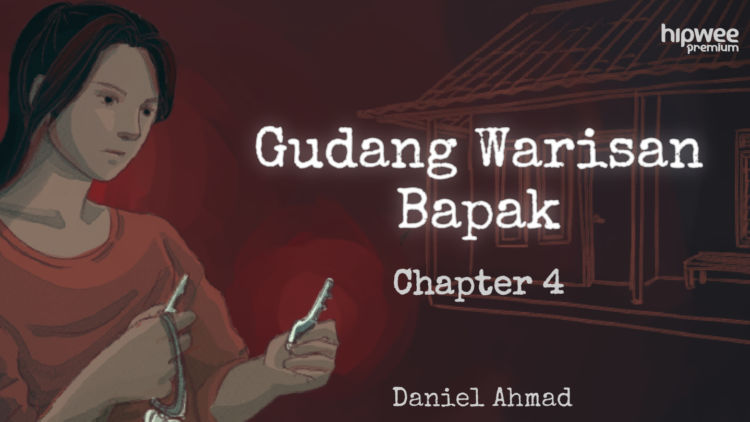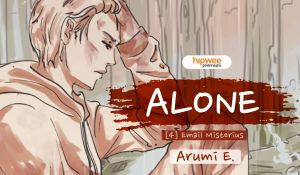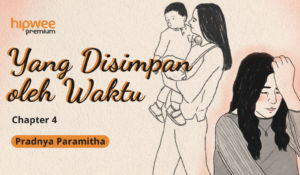“Bapak!” seruku.
Pintu kamar bapak terbuka. Langkah cepatku melambat. Setelah menggebu-gebu pergi ke dapur, kini aku malah enggan mendekati gudang itu. Gelap sekali. Lalu, di lantai gudang kulihat sesuatu yang menyala. Dua titik merah terang. Aku benci memikirkannya, tapi sepintas mirip bola mata yang berkedip-kedip dalam gelap, menatap tajam ke arahku.
“Zara,” erang bapak dari dalam kamar.
“Ba-bapak? I-itu beneran Bapak, kan?”
“Zara, sini, nak!”
Aku yakin itu suara bapak. Hanya saja, akal sehat ini menahanku untuk mendekat. Seolah berbisik, “Jangan ke sana, Zara. Tidakkah kau menangkap sinyal berbahaya dari tempat itu?” Tentu saja aku merasakannya. Lantas apa aku harus kabur dan mengacuhkan bapak?
Dari suaranya barusan, bapak seperti sedang kesakitan. Aku memang anak tiri, tapi pria di dalam kamar itu adalah satu-satunya orang yang saat ini bisa kusebut ayah. Tekadku sudah bulat. Kupaksa kaki ini melangkah. Kuterobos segala keraguan dan ketakutan.
“Bapak,” panggilku.
Kini aku sudah dua langkah di depan pintu. Semakin jelas terlihat bahwa yang saat ini sedang telentang di lantai adalah bapak.
“Astaghfirullah!”

Bapak dan Zara/ Illustration by Hipwee
Kubergegas menghampiri. Tanpa ragu kuraih kepala bapak lalu menidurkannya di pangkuan. Sekujur tubuh bapak lemas, tak ada tenaga untuk sekadar duduk. Kondisi ini membuatku bingung harus bagaimana. Meski sekarang bapak sangat kurus dan terasa ringan, tapi dengan tubuhku yang jauh lebih kecil dari bapak, mustahil rasanya menggendong bapak ke luar atau sekadar menidurkannya kembali di ranjang kardus itu.
“Bapak kenapa? Jatuh, ya?” isakku.
Kulihat makanan yang kusiapkan tadi sore masih utuh di nampan. Bapak belum makan. Terpikir olehku untuk menghubungi kak Sabit, tapi ponselku ada di kamar.
“Bapak tunggu di sini, Zara telponin Kak Sabit dulu, ya.”
Kuraih tumpukan kain di ranjang yang bapak gunakan sebagai bantal, kuletakkan di lantai, lalu perlahan kutidurkan bapak di sana. Aku berlari ke kamar. Pikiranku kacau. Bahkan saat jempol kakiku tersandung kaki meja makan pun, secara otomatis otak ini mengabaikan sakitnya. Begitu sampai di kamar, kuraih ponsel, kujelajahi daftar nomor, lalu kucoba menelepon Kak Sabit.
“Angkat, dong! Sialan!” umpatku.
Terdengar peringatan bahwa nomor yang kutuju sedang tidak bisa menerima panggilan. Tak mau buang waktu, kucoba menghubungi semua nomor kakak-kakakku, sialnya, tidak satu pun dari mereka yang menjawab.
“Mereka ini kenapa, sih?” geramku. “Apa sebaiknya aku minta bantuan tetangga saja? Oh, ya, Pak Sukril. Aku ke rumah Pak Sukril sa—“
Suaraku terputus. Rasanya leher ini seperti dicekik sesuatu kala kuberbalik untuk ke luar dan mendapati seseorang tengah berdiri di pintu kamar.
“Si-siapa kamu?”
Sosok itu nyata. Kali ini aku yakin mataku tak salah lihat. Dia tinggi sekali. Mungkin jika berdiri tegak dan tidak membungkuk seperti itu, kepalanya bisa melewati bingkai pintu. Melihatnya dari jarak sedekat ini telah memperjelas banyak hal, salah satunya bahwa dia tidak berbaju merah, tapi kulit di sekujur tubuhnya memang berwarna merah gelap. Tak ada kain yang menempel di sana. Satu-satunya corak di kulitnya berasal dari urat-urat yang bertonjolan. Lalu, wajahnya … bagaimana aku mendeskripsikan kengerian ini? Ada banyak benjolan hitam sebesar kelereng di wajahnya. Tak kulihat hidung atau pun mulut, hanya mata hitam dengan pupil merah terang yang melotot.

Sosok tinggi/ Illustration by Hipwee
Kedua tangan dengan jemari kurus itu menerobos masuk. Mencoba menggapaiku yang kini berdiri kaku. Lalu, saat kupikir tak ada hal lain yang bisa mengejutkanku, sosok itu memegangi kedua pundakku, lalu dengan jelas sekali membisikkan sesuatu.
ZARA, MAAFKAN BAPAK, NAK.
***
Innalillahi, wa innailaihi rajiun
Bapak meninggal di usia 66 tahun setelah bertahun-tahun berjuang melawan penyakitnya. Ia meninggalkan lima orang anak dan tiga orang cucu. Dari keenam orang anaknya, hanya aku, anak tirinya yang benar-benar ada di samping bapak saat ia menghadapi detik-detik terakhir. Hanya aku yang menjadi saksi betapa menyedihkan dan menyakitkannya saat-saat terakhir almarhum, hanya aku pula yang saat ini benar-benar kelihatan sangat sedih. Sungguh, aku tak mengerti garis kelegaan yang tergurat jelas di wajah kakak-kakakku ini.
Satu-satunya hal yang kusesali adalah, aku tak sempat membimbing bapak membaca syahadat, karena semalam, begitu aku berhasil menghubungi Kak Rohim dan buru-buru kembali ke dapur, bapak sudah tidak lagi bernapas. Ia meninggal di lantai gudang yang kotor, dengan kondisi yang benar-benar menyedihkan.
Siang ini kami berlima kumpul di dapur. Meja makan berubah jadi meja diskusi. Tak ada makanan, hanya air putih dan hening yang tak kunjung pecah sejak satu jam lalu. Kak Sabit, Kak Imah, Kak Naura, dan Kak Rohim sedang sibuk dengan ponsel masing-masing. Mereka melansir kabar tentang meninggalnya bapak ke sanak saudara yang jauh.
“Halo, iya, Mas. Bapak dimakamkan di sini. Tadi sekitar jam enam pagi. Alhamdulillah tetangga masih banyak yang peduli. Tadi Ustaz Hamis yang mimpin salat sama mandiin jenazahnya.”
Begitu kutipan obrolan telepon Kak Sabit, entah siapa yang ada di ujung sana. Aku tidak mau tahu. Usai menelepon, Kak Sabit melipat kedua tangannya di meja makan. Sepertinya dia hendak mulai bicara serius.
“Utang-piutang bapak biar aku yang urus,” ujar Kak Sabit. “Masih ada tiga yang belum aku lunasi dan ada sekitar enam orang yang belum aku tagih.”
“Yang di bank gimana?” tanya Kak Naura.
“Jaminan utang di bank kan pakai tanah di belakang madrasah itu. Sekarang masih disewakan. Sesuai kesepakatan, tanah itu kita jual, hasilnya kita bagi.”
“Tapi, bapak inginnya tanah itu dibagi-bagi, kan? Biar anak-anaknya kumpul di sana,” sahut Kak Rohim.
“Ya, aku tahu, tapi sekarang Naura dan Imah sudah berkeluarga. Mereka sudah punya rumah sendiri-sendiri.”
Kak Rohim terdiam. Tak ada protes lebih lanjut darinya. Percakapan berlanjut ke pembagian warisan. Kak Sabit membacakan dengan detail isi dari kertas-kertas yang sejak tadi ia genggam itu. Tak ada gunanya aku mengikuti dengan saksama, karena rasanya aku hanya jadi penonton di sini. Dukaku masih belum reda. Aku masih saja memikirkan bapak dan tak sedikit pun terbesit tentang warisan.
“Tahlil besok di rumah Rohim saja. Lebih dekat, kan? Tenang saja, nanti aku dan kakakmu yang bantu tiap hari.”
Kak Rohim mengangguk. Ia juga tidak protes tentang usulan itu. Meski sebenarnya aku kasihan karena setahuku Kak Rohim juga masih ngontrak. Semoga saja Kak Sabit dan yang lain benar-benar membantu.

Membicarakan warisan/ Illustration by Hipwee
Sejujurnya aku mulai merasa tidak nyaman berada dalam lingkaran ini. Merasa tidak dibutuhkan, aku pun pamit pergi ke kamar.
“Mau ke mana, Ra?” tanya Kak Imah.
“Mau rapihin beras sama gula dari tetangga. Sekalian bersihin ruang tamu. Bentar lagi pasti banyak yang ngelayat,” ucapku.
“Duduk dulu,” pinta Kak Sabit. “Ada hal penting yang mau kami sampaikan sama kamu.”
Baiklah, jika ini penting, kenapa tidak dari tadi saja? gerutuku dalam hati.
Kak Rohim mengangguk padaku, memberi isyarat agar sebaiknya aku menurut. Aku duduk kembali dengan enggan. Dengan sebuah embusan napas kesal.
“Ya, ada apa?” tanyaku ketus.
Kak Sabit merogoh kantong kemejanya, kemudian ia menyodorkan sesuatu padaku. Sebuah kunci perak dengan gantungan kunci menyedihkan yang terbuat dari tali rafia. Sontak aku bertanya-tanya, apa maksudnya?
“Kunci apa ini?”
“Sebelum meninggal, bapak berwasiat agar memberikan rumah dan tanah ini sama kamu.”
“Apa?” tanyaku nyaris teriak.
Entah aku terkejut karena sebagai anak tiri aku masih kebagian warisan atau aku terkejut karena warisan ini adalah satu-satunya hal tidak aku inginkan. Maksudku, siapa yang mau tinggal di sini? Aku tahu, aku bisa menjualnya kapan pun aku mau, tapi untuk saat ini aku tidak mau berpikir sejauh itu.
“Ini kemauan bapak, Ra. Terimalah. Kami juga sudah setuju, kok.”
Mereka semua mengangguk, hanya Kak Rohim saja yang tampak membuang muka. Entah apa maksudnya. Tidak senangkah dia dengan keputusan ini? Aku tahu, di antara kami berlima, Kak Rohimlah yang paling butuh tempat tinggal.
“Aku harus kembali ke kota besok, aku nggak ada waktu ngurus rumah ini—“
“—Nggak apa-apa, ada Rohim yang bakal ngurus rumah ini, ya, kan, Him?” ujar Kak Naura.
“I-iya, kamu bisa pulang ke sini kalau lagi liburan,” jawab Kak Rohim sedikit kikuk.
“Ya udah kalau gitu, ini kuncinya kasih ke Kak Rohim aja!” aku menggeser kunci dihadapanku ke hadapan Kak Rohim.
“Oh, itu bukan kunci rumah, Ra,” kata Kak Sabit.
“Terus?”
“Ini kunci kamarmu yang lama. Karena sekarang ini rumah kamu, jadi semua yang ada di rumah ini juga punya kamu. Termasuk semua yang ada di dalam kamar itu,” tutur Kak Sabit.
Seketika semua orang memalingkan wajah. Seolah mereka tak berani menatapku, atau takut kalau-kalau aku menanyakan lebih lanjut tentang isi dari kamar itu.
-bersambung


![]()